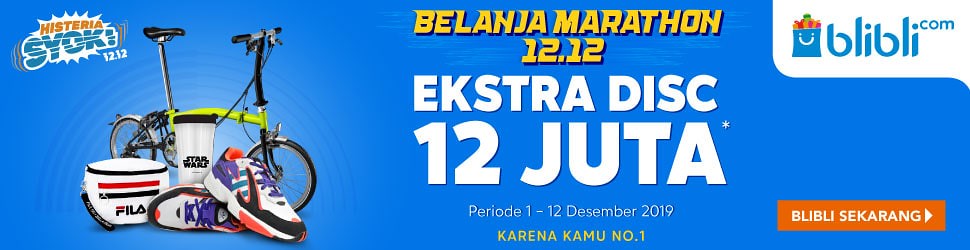MAMIRA.ID, Bondowoso – Di kawasan Jawa Timur, terdapat satu bahasa daerah yang penuturnya hampir sepertiga dari jumlah kabupaten di provinsi tersebut. Bahasa yang dimaksud ialah Bahasa Madura. Tak hanya bahasanya, namun sekaligus juga budayanya. Bahkan jika dibandingkan dengan pulau Madura sendiri—selaku pusat bahasa dan budaya pulau garam—yang terdiri dari empat kabupaten di dalamnya, di provinsi ujung timur Pulau Jawa itu, jumlah kabupaten yang menggunakan Bahasa Madura dalam kesehariannya justru jauh lebih banyak.
Nah, kawasan yang terdiri sedikitnya enam kabupaten di Jawa Timur selaku penutur bahasa Madura terbanyak ini dikenal dengan sebutan daerah Tapal Kuda. Sebutan tapal kuda sendiri sejatinya tidak memiliki benang merah dengan Madura, namun karena bentuk kawasan tersebut dalam gambar peta yang mirip dengan bentuk tapal kuda.

Hingga dewasa ini ada sekitar tujuh kabupaten di Jawa Timur yang masuk kawasan Tapal Kuda. Yaitu Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi. Secara tradisi, daerah ini merupakan nama kedua dari Blambangan, yakni kawasan yang sudah ada sejak masa kerajaan Majapahit.
Masuknya bahasa Madura di kawasan Tapal Kuda memiliki mata rantai kisah yang sedikit panjang. Namun secara garis besar, kawasan ini mulai “diisi” bibit orang Madura sejak waktu yang relatif lama dari masa kini. Secara historis, peristiwa tersebut terjadi kurang lebih sejak abad 18 Masehi.
Sejak saat itulah, Madura, lebih tepatnya bahasanya mulai menjadi lingua franca, dengan melampaui garis-garis teritorialnya. Bahkan dalam perkembangannya, bahasa Madura justru mendesak bahasa Jawa yang awalnya menjadi bahasa komunikasi di kawasan Tapal Kuda.
Peristiwa masuknya warga Madura ke Tapal Kuda pada abad 18, bisa dikatakan sejak masa pemerintahan Raden Ahmad atau Pangeran Jimat (gelar lainnya ialah Pangeran Cakranegara III). Pangeran ini merupakan Adipati Sumenep pada 1721-1744 M.

Secara genealogi, sang adipati ini merupakan paduan darah penguasa Sumenep dan Pamekasan. Dalam sebuah insiden, Pangeran Jimat secara de fakto juga sempat memegang kendali atas pemerintahan Pamekasan. Nah, sejak saat itu, beberapa daerah di kawasan Tapal Kuda dimasukkan pula sebagai bagian dari Sumenep. Sehingga banyak orang Madura yang dikirim ke sana untuk membabat kawasan.
Sejak saat itu, “eksodus kecil” warga Madura ke wilayah Tapal kuda membentuk warna baru di sana. Tradisi, budaya, sekaligus—seperti yang disebut di muka—bahasa Madura juga hidup dan mengakar di kawasan tersebut.
Sekilas Besuki-Situbondo-Bondowoso
Sepeninggal Pangeran Jimat, di wilayah Besuki muncul tokoh Pate Alos sebagai Patih di Besuki. Pate Alos ini bersusur galur pada keluarga ulama di Pamekasan. Leluhurnya Raden Abdullah berasal dari Pademawu, Pamekasan.
Puluhan tahun berikutnya, Besuki dibentuk kadipaten dengan Raden Bambang Sutiknya sebagai Adipati Pertama. Sutiknya yang bergelar Pangeran Adipati Ario Prawiroadiningrat I itu merupakan cucu Panembahan Sumolo, Raja Sumenep (1762-1811). Peristiwa itu terjadi pada 1819 Masehi.
Jadi sebelum muncul kebijakan kolonial tentang Maduranisasi (pemilihan bupati dari etnis Madura) pada abad 19, Pangeran Jimat telah menancapkannya sejak abad 18.
Sutiknya yang cerdas lantas melakukan pembenahan-pembenahan penting. Pembenahan pertama ialah di bidang administrasi. Meski belum ada penelitian utuh tentang peran Sutiknya dalam reformasi pemerintahan di Besuki, ia diakui berperan penting dalam sisi birokrasi politik di sana.
Langkah penting selanjutnya, Sutiknya berhasil membangun Kota Besuki hingga menjadi kota yang paling maju dan ramai di wilayah ujung timur Jawa. Dalam sebuah catatan, beliau berupaya menaikkan taraf hidup rakyat dengan membangun Dam Sluice dan memperluas sawah.
Sutiknya juga tercatat melakukan pembuatan dan perbaikan jalan yang menghubungkan Kabupaten Besuki dengan daerah Besuki pedalaman. Tak hanya itu, Sutiknya juga membuka kelas sekolah untuk anak bangsawan, orang Eropa dan bumiputera. Sekolah tiga kelas dibangun dengan mendatangkan guru orang Belanda.

Sekitar 1844, Sutiknya mangkat. Beliau diganti oleh Raden Wongso putranya, dengan gelar Raden Adipati Ario Prawiroadiningrat (dikenal dengan Prawiroadiningrat II). Diangkat pula putra Sutiknya lainnya, yaitu Raden Pandu sebagai penguasa Panarukan kemudian pindah ke Situbondo.
Wongso Prawiroadiningrat dan Pandu dikenal progressif. Di masa Wongso dan Pandu, banyak karya yang cukup menonjol, seperti berdirinya Pabrik Gula (PG) di Kabupaten Situbondo, dimulai dari PG Demas, PG Wringinanom, PG Panji, dan PG Olean.

Lambat laun, kemajuan Besuki menurun, dan Situbondo menonjol. Hingga pasca Wongso, pusat pemerintahan dipindah ke Situbondo, dan Pandu diangkat sebagai bupati pertama Situbondo dengan gelar Kangjeng Raden Tumenggung Ario Pandu Suryoatmojo.
Sementara di kawasan lain, seperti Bondowoso, dibabat oleh bangsawan asal Pamekasan. Adalah Ronggo Mas Ngabehi Kertonegoro, Ronggo pertama dari kawasan yang awalnya bernama Blindungan itu. Sebelum menjadi ronggo, Kertonegoro berpangkat demang dan dinaikkan statusnya sebagai ronggo oleh Pangeran Sutiknyo, Adipati pertama Besuki.
Kertonegoro sendiri, bersusur galur pada Raden Adipati Ario Adikoro IV (Raden Ismail), Adipati Pamekasan yang gugur di Bulangan pada peristiwa Ke’ Lesap (1750 Masehi).
Di masa-masa berikutnya, para pembesar lainnya di kawasan Tapal Kuda, masih berasal dari keluarga besar bangsawan Sumenep-Pamekasan. Begitu juga dalam proses pembumian Islamisasi di sana yang banyak melibatkan tokoh-tokoh ulama asal Madura, khususnya dari Madura Timur dan Pamekasan, yang hingga saat ini menjadi cikal-bakal pesantren-pesantren besar di sana.
(bersambung)